Ketika Api Sumpah Pemuda Mencari Jalan Pulang di Politik Indonesia
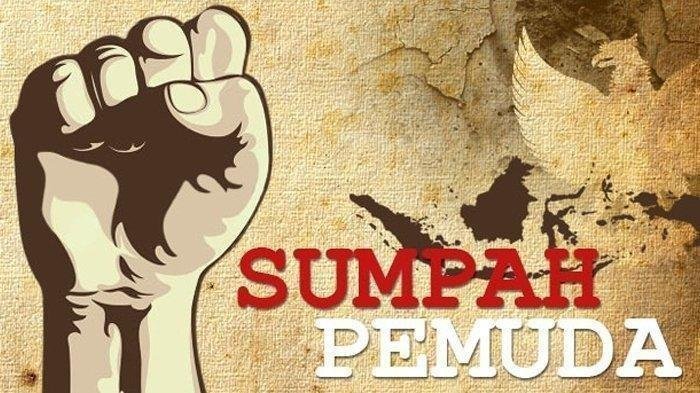 Api Sumpah Pemuda. (Istimewa)
Api Sumpah Pemuda. (Istimewa)PRIORITAS, 28/10/25 (Jakarta): Di tepi Pantai Kilometer Nol, Sabang, sekelompok mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) tampak sibuk memungut sampah plastik. Di bawah terik matahari, mereka menulis sejarah dengan caranya sendiri—tidak dengan orasi atau upacara, tetapi lewat aksi nyata.
Bagi generasi 1928, Sumpah Pemuda adalah ikrar yang menyatukan bangsa. Bagi generasi hari ini, semangat itu menemukan bentuk baru: kepedulian terhadap lingkungan, solidaritas sosial, dan keberanian mengkritisi kekuasaan.
Namun, satu pertanyaan besar tetap menggema: masihkah api itu menyala di dada generasi muda Indonesia?
Dari idealisme ke kenyataan politik
Dikuip dari catatan Hamka Hendra Noer, Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diterbitkan Republika.co.id, bahwa sembilan puluh tujuh tahun setelah ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan, wajah politik Indonesia berubah cepat—namun tidak selalu ke arah yang diimpikan para pendahulu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2024, jumlah pemuda berusia 16–30 tahun di Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa, setara dengan sekitar 23% dari total populasi (berdasarkan proyeksi BPS tahun 2024). Angka ini merupakan sekitar seperlima dari jumlah penduduk Indonesia. Lebih dari separuh pemilih nasional kini di bawah usia 40 tahun. Namun, ironisnya, hanya 12 persen anggota DPR berasal dari kelompok usia tersebut (CSIS Political Index, 2023).
Kesenjangan antara potensi demografis dan representasi politik ini menjadi alarm bagi regenerasi nasional. “Banyak anak muda pintar, tapi sistemnya tidak membuka ruang bagi regenerasi sejati,” ujar Hamka Hendra Noer.
Ia menyebut, politik Indonesia masih dikuasai patronase. Kader muda dijadikan wajah kampanye, bukan pengambil keputusan. “Mereka diminta tampil, tapi tidak diajak berpikir,” katanya.
Riset Mietzner dan Aspinall (2024) menunjukkan, lebih dari 70 persen kader muda gagal menembus posisi strategis karena dominasi elite senior. Fenomena ini membenarkan hukum klasik Robert Michels—“Iron Law of Oligarchy”—bahwa setiap organisasi yang mapan cenderung dikuasai oleh sedikit orang yang mempertahankan kekuasaan.
Bahkan, CSIS mencatat hanya 18 persen partai yang memiliki program kaderisasi aktif bagi anggota muda. Akibatnya, idealisme pemuda sering teredam sebelum tumbuh menjadi kekuatan perubahan.
“Padahal, kalau generasi 1928 melawan kolonialisme fisik, generasi sekarang sedang melawan kolonialisme moral: apatisme dan pragmatisme,” tulis Hamka.
Namun, di tengah kelesuan politik, ada tanda-tanda kebangkitan. Gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi, Climate Rangers Indonesia, dan Pemuda Desa Membangun menunjukkan bahwa energi perubahan masih ada—meski tak lagi dalam bendera partai.
Katadata Insight Center (2024) mencatat, 63 persen pemuda aktif dalam kegiatan sosial dan advokasi, meskipun hanya 21 persen yang bergabung dengan partai politik. Fenomena ini menunjukkan pergeseran ke arah politik substantif, yakni politik yang berbasis nilai, etika, dan aksi sosial nyata.
“Politik hari ini bukan soal umur, tapi nurani,” kata Hamka. “Kepemimpinan muda yang sejati bukan hanya muda secara usia, tapi juga muda dalam semangat—berani berpikir, terbuka terhadap kritik, dan tegak bermoral.”
Regenerasi politik bukan hal mustahil. Di Thailand, Pita Limjaroenrat, pemimpin partai Move Forward, berhasil menarik 45 persen pemilih muda. Malaysia menurunkan usia pemilih dan kandidat legislatif lewat kebijakan Undi 18, meningkatkan partisipasi pemuda hingga 71 persen pada Pemilu 2022 (SPR, 2023).
Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan gerontokrasi politik—di mana kekuasaan diwariskan, bukan diperjuangkan. Survei Indikator Politik (2024) menyebut, hanya 32 persen pemuda yang percaya partai merepresentasikan aspirasi mereka.
Tanpa reformasi struktural dan etika politik, idealisme pemuda hanya akan menjadi slogan tahunan di setiap 28 Oktober.
Menjadi subjek, bukan sekadar simbol
Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti di spanduk dan seremoni. Ia harus hidup dalam keberanian generasi muda untuk menjadi subjek moral demokrasi—bukan sekadar objek kampanye.
Amartya Sen (2009) pernah menulis bahwa keadilan politik bergantung pada kemampuan masyarakat memperbaiki institusinya. Artinya, perubahan tidak cukup dituntut, tapi harus dibangun bersama.
“Kalau generasi 1928 melahirkan Indonesia merdeka, maka generasi 2025 harus melahirkan Indonesia yang berintegritas,” tulis Hamka mengakhiri refleksinya.
Dari pantai Sabang hingga ruang-ruang digital, suara generasi muda kini bergema lagi. Mereka tidak hanya meneriakkan sumpah, tetapi menagih janji. Bahwa politik bukan milik yang tua, tetapi milik mereka yang masih berani bermimpi dan berbuat untuk bangsa. (P-Rep./bwl)
















No Comments